Memahami Nama ‘Hu’/’Huwa’:
Dia Yang Tak Bisa Diliputi Nama
A. Sebutan Tuhan
Sahabat-sahabat, kadang kita terlalu cepat ‘memagari diri’ dari
istilah-istilah yang kita anggap tidak berada dalam domain yang sama
dengan agama kita. Terlalu cepat ‘mengkafirkan’. Bukan mengkafirkan
orang lain, tapi mengkafirkan bahasa (lain). Dengan memagari diri
seperti ini, apalagi dengan didahului prasangka, maka dengan sendirinya
kita akan semakin sulit saja memahami hikmah kebenaran yang Dia
tebarkan di mana-mana.
Padahal, dalam Qur’an pun Allah menjelaskan bahwa beragam bahasa adalah tanda dari-Nya juga.
“Dan diantara ayat-ayatnya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang berilmu (‘Alimiin).” Q.S. 30 : 22.
Jika ada orang menyebut tuhannya sebagai Yehovah, Eloh, Eloheim, atau Adonai,
mekanisme dalam pikiran kita mendadak seperti mencipta imaji-imaji
bahwa ada banyak tuhan yang sedang berjejer, sesuai urutan sesembahan
yang ada sepanjang masa. Ada tuhan yang disebut Yehovah, Eloheim, Jahveh, Brahma, Manitou, Zeus, Allah, Tuhan Alah,
dan lain sebagainya. Sedangkan yang kita sembah adalah yang disebut
Allah, yang lainnya bukan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan
Tuhan kita dan agama kita. Pokoknya thoghut, atau kafir.
Benarkah begitu? Bukankah Tuhan hanya satu? Bukankah ‘Laa ilaaha Ila’Llah’ artinya tiada Tuhan selain Allah? Wallahu ‘alam,
meski saya mengerti bahwa Tuhan hanya satu, tapi saya belum mengetahui
secara total makna lahiriyah maupun batiniyah dari kalimat syahadat itu.
Tapi setidaknya, bukankah cara berfikir yang seperti tadi juga berarti
bahwa tanpa sadar pikiran kita telah menyejajarkan Dia dengan
selain-Nya? Atau, secara halus dan tersamar sekali, itu artinya kita
masih mengakui bahwa ada banyak entitas dalam satu himpunan tuhan, dan
Allah adalah salah satu dari yang ada dalam himpunan itu. Bukankah itu
keterlaluan?
Istilah ‘Allah’ sudah ada sejak sebelum Al-Qur’an turun. Sebelum junjungan kita Rasulullah menerima wahyunya yang pertama, bangsa Arab sudah menggunakan kata- kata ‘demi Allah’ jika mengucapkan sumpah. Hanya saja, mereka juga sering menyebut nama patung-patung mereka, ‘demi Lata’ atau ‘demi Uzza’, ‘demi punggung istriku’, atau bahkan ‘demi kuburan ibuku’, dalam sumpah mereka.
Istilah ‘Allah’ sudah ada sejak sebelum Al-Qur’an turun. Sebelum junjungan kita Rasulullah menerima wahyunya yang pertama, bangsa Arab sudah menggunakan kata- kata ‘demi Allah’ jika mengucapkan sumpah. Hanya saja, mereka juga sering menyebut nama patung-patung mereka, ‘demi Lata’ atau ‘demi Uzza’, ‘demi punggung istriku’, atau bahkan ‘demi kuburan ibuku’, dalam sumpah mereka.
Kapan istilah ‘Allah’ pertama kali dikenal manusia? Tidak tahu
persis. Diperkirakan tidak akan jauh dari periode kemunculan agama
Islam yang dibawa Rasulullah di tanah Arab. Tapi apakah berarti, pada
periode sebelum itu, Allah diam saja di langit sana, dan tidak
memperkenalkan diri-Nya? Rasanya kok tidak demikian ya. Saya
suka bertanya-tanya, misalnya dengan nama apa Allah mengenalkan diri-Nya
pada nabi Ya’kub as dan nabi Musa as, nabi bangsa Bani Israil? Karena
pada kenyataannya, bangsa yahudi sekarang tidak menyebut nama-Nya dengan
sebutan ‘Allah’ yang sesuai dengan bahasa Arab.
Kitab suci dari Allah yang kita kenal ada empat: Taurat, Zabur,
Injil, dan kitab penutup dan penyempurna semuanya, Al-Qur’an. Taurat,
atau Torah, turun kepada Nabi Musa as. Karena Musa adalah
orang Bani Israil, tentu kitab yang turun pun berbahasa mereka, Ibrani.
Demikian pula Zabur, Injil, dan Al-Qur’an. Semua turun dan disampaikan
dengan bahasa penerimanya.
Jadi, apakah salah jika orang yang kebetulan beragama lain, menyebut
nama Allah dengan nama yang turun pada bahasa kitab mereka? Apakah itu
Tuhan yang lain? Belum tentu. Sekali lagi, kita tidak boleh terlalu
cepat ‘mengkafir-kafirkan’, termasuk mengkafirkan bahasa dan istilah.
Ada banyak sekali irisan kemiripan bahasa-bahasa agama dalam sejarah. Sebagai contoh, nama ‘Allah’, sangat mirip dengan ‘Eloh’. Dalam kitab-kitab Ibrani, Tuhan disebut sebagai ‘Eloheim’. Dari asal kata ini, kita mengerti misalnya arti kata ‘betlehem.’ Dari asal katanya, Bethel dan Eloheim.
‘Bethel’ bermakna rumah, dan ‘Eloheim’ adalah Allah. Rumah Allah. Jika
demikian, apa bedanya kata ‘Betlehem’ dengan ‘Baytullah’?
Juga ‘Yehova’ atau ‘Yahwe’, sangat mirip dengan ‘Ya Huwa’, Wahai Dia (yang tak bernama). Yang agak ‘mencurigakan’, adalah inti ajaran Socrates, ‘Gnothi Seauthon’,
yang artinya adalah ‘Kenalilah Dirimu.’ Dari segi makna, ini sangat
mirip dengan inti hadits yang sering diulang-ulang oleh para sahabat
Rasulullah maupun para sufi terkemuka, ‘man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa Rabbahu,’ mereka yang ‘arif tentang dirinya, akan ‘arif pula tentang Rabb nya.’ Esensinya sangat mirip: mengenal diri.
Dan sebuah fakta yang tak kalah menariknya, sejarah mencatat bahwa
Socrates adalah guru dari Plato, Plato guru dari Aristoteles, dan
Aristoteles adalah guru dari Alexander of Macedon. Sosok yang
terakhir ini oleh sebagian ahli tafsir disamakan dengan Iskandar
Dzulqarnayn, sosok panglima yang namanya diabadikan dalam Al-Qur’an.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua tuhan sama saja, yang
berbeda hanya namanya. Atau dewa pada tiang totem yang disembah bangsa
indian apache adalah Allah juga. Bukan begitu. Saya hanya mengatakan
bahwa kita sebaiknya jangan terlalu ‘alergi’ dengan kata-kata agamis
dari agama lain. Kita harus berhati-hati sekali untuk ‘mengkafirkan’
istilah. Sebab kalau ternyata salah, maka artinya kita ‘mengkafirkan’
sebuah hikmah atau sebuah tanda dari-Nya. Maka kita akan semakin jauh
saja dari kebenaran.
Bukankah Allah pasti menyebarkan jejak-Nya di mana-mana, sepanjang
zaman? Dan jangan berfikir bahwa Allah hanya pernah dan hanya mau
‘muncul’ di agama kita saja. Ini berarti kita, sebagai makhluk,
berani-berani menempatkan Allah dalam sebuah himpunan, ke sebuah konsep
di dalam kepala kita. Himpunan deretan tuhan, atau himpunan kelompok
agama.
Allah adalah Tuhan. La Ilaha Ilallah. Dia ada di luar
himpunan apapun. Dia tak beragama, dan tidak memeluk agama apapun.
Karena itu, kita jangan berfikir, baik sadar maupun tidak, bahwa Allah
‘beragama Islam’.
Agama diciptakan-Nya sebagai jalan untuk memahami-Nya, memahami
kehidupan, dan memahami diri ini. Segala sesuatu Dia ciptakan dan Dia
akhiri. Maka Allah adalah sumber dan akhir segalanya. Dua asma- Nya
adalah ‘Al-Awwal’ dan ‘Al-Akhir’. Ini pun sebuah
kebetulan yang menarik, karena bangsa Yunani kuno, bangsanya Socrates
dan Plato, eyang guru dari Alexander tadi, juga menyebut salah satu nama
yang dimiliki Tuhan mereka sebagai ‘Alpha Omega’, berarti ‘Yang Awal dan Yang Akhir’ (Alpha = Alif = huruf awal dalam alfabet yunani dan arab, simbol ‘awal’; sedangkan Omega = huruf terakhir dalam alfabet yunani, simbol ‘akhir’). Kemiripan yang sangat menarik, ya?
B. Asma-asma Allah.
Istilah ‘Allah’ sendiri adalah ‘hanya’ sebuah asma. Itu hanya nama
dari sebuah entitas. Namun ‘Hu’, atau ‘Dia’, adalah sebutan bagi sebuah
zat, sebuah entitas, yang tertinggi. Tak terbandingkan, tak terukur,
tak terperi. Lalu apakah kita, sebagai makhluk, memungkinkan untuk
menempatkan Dia ke dalam kepala kita, menaruhnya ke dalam sebuah konsep
‘nama’? Tentu tidak. Dia, secara utuh, secara menyeluruh, secara real,
sesungguhnya tak bernama. Tak ada apapun yang bisa membungkus-Nya,
termasuk sebuah nama.
Lalu untuk apakah, atau nama-nama siapakah, yang berjumlah sembilan
puluh sembilan sebagaimana diperkenalkan dalam Al-Qur’an, dan disusun
sebagai ‘asma’ul husna’? Nah, itu adalah bukti begitu penyayangnya Dia pada makhluknya yang satu ini, manusia.
Penjelasannya begini. Dia Yang Tertinggi jelas tak mungkin dibungkus
atau terliputi oleh apapun, termasuk sebuah nama. Tapi Dia bersedia
‘menurunkan derajat-Nya’ demi supaya lebih dimengerti oleh manusia.
Maka Dia memperkenalkan diri-Nya, bagi mereka yang ingin mengenal-Nya
di tahap awal, dengan memisalkan dirinya dengan nama-nama sifat
manusia. Memisalkan diri-Nya dengan nama-nama yang memungkinkan untuk
dideskripsikan dalam bahasa manusia.
Ambil contoh, Ar-Rahmaan (Maha Pengasih) atau Ar-Rahiim
(Maha Penyayang). Kita bisa memahami makna dua kata ini, karena nama
sifat-sifat ini, pengasih dan penyayang, adalah nama sifat yang juga
ada pada manusia. Tapi dari segi makna, kedua kata ini dalam
memperkenalkan nama sifat-Nya sebenarnya telah mengalami degradasi makna
yang amat sangat.
Maha Pengasih, atau Ar-Rahmaan, adalah ‘hanya’ bahasa
manusia yang paling memungkinkan untuk menggambarkan salah satu
sifat-Nya. Tapi kedalaman makna istilah ini telah berkurang jauh
sekali, karena Dia, yang Tak Terperi, memisalkan diri-Nya dengan
istilah manusia yang jelas tak memadai untuk melukiskan diri-Nya yang
tak terbatas. Dalam asma’ul husna, misalkan istilah ‘Ar-Rahim’,
sebenarnya ‘hanya’ merupakan sebuah istilah yang masih memungkinkan
untuk bisa terpahami oleh manusia. Sifat Penyayang-Nya yang asli, yang
real, yang tidak bisa dimisalkan dengan bahasa manusia, adalah jauh,
jauh, jauh lebih penyayang lagi, melebihi apa yang tergambar pada
sepotong kata ‘Ar-Rahim’.
Demikian pula untuk ke-98 asma asma Allah yang lain. Semua nama-nama
tersebut, sebenarnya mengalami degradasi makna yang sangat jauh dari
aslinya, demi supaya terpahami oleh kita, manusia. Sifatnya yang asli,
tak terkira jauhnya melebihi apa yang mampu tergambarkan oleh sepotong
kata dalam bahasa kita, manusia.
Allah telah berkenan ‘merendahkan diri-Nya’ ke dalam nama sifat-sifat
manusia, yang jauh, jauh lebih rendah dari kedudukan-Nya yang asli. Ia
bersedia dipanggil dengan bahasa kita. Ini sebuah bukti
kasihsayang-Nya yang amat sangat. Bisakah kita membayangkan, misalnya
ada seorang raja yang kerajaannya mencakup lima benua, lalu bersedia
turun berjalan di pasar kumuh dan mau dipanggil dengan bahasa pasar,
seperti ‘Lu’, ‘Sia’, atau ‘Kowe’? Raja tentu akan
sangat murka. Tapi Dia, Allah, tidak. Meskipun Dia Maha Tinggi
kedudukannya, tapi Dia bahkan bersedia memperkenalkan diri-Nya lebih
dahulu (!), dan membahasakan diri-Nya dengan bahasa manusia, dan
mencontohkan asma-Nya dengan sifat manusia.
‘Dia’ yang asli, sesungguhnya tidak bernama. Lalu istilah ‘Allah’ itu apa? Istilah itu ‘hanyalah’ bagian dari asma’ul husna, pada urutan yang pertama.
Istilah ‘Allah’, menurut seorang ahli hikmah, sebenarnya sebuah simbol juga. Menurutnya, istilah ‘Allah’, yang terdiri dari:
‘alif’, ‘lam’, ‘lam’ dan ‘ha’,
sesungguhnya merupakan singkatan dari kata bahasa Arab:
‘Al/Alif – li – li – hu/huwa’.
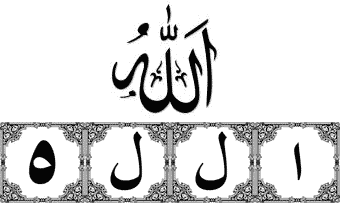
‘Al’ dalam bahasa Arab bermakna kata ganti tertentu, maknanya sama seperti ‘The’ dalam bahasa Inggris, atau seperti ‘El’ dalam bahasa Ibrani dan bahasa Spanyol. Maknanya, katakanlah, ‘sesuatu’. Huruf ‘Alif’ bermakna ‘sesuatu yang tegak’, ‘Allah’, atau bisa juga ‘yang mengawali’, mirip seperti alpha dalam aksara Yunani. Kata ‘Li’ dalam bahasa Arab bermakna ‘bagi sesuatu’, dan dalam lafaz ‘Allah’ kata ini diulang dua kali. Sedangkan ‘hu’ atau ‘huwa’ bermakna ‘Dia’.
Jadi lafaz ‘Allah’, kata yang di dalam Al-Qur’an paling sering
dipakai-Nya untuk menyebut diri-Nya, sebenarnya sama sekali tidak
mencakup keseluruhan zat-Nya. Lafaz ‘Allah’ sebagai simbol, sebenarnya
justru mempertegas bahwa ‘Dia’ adalah tak bernama. Mengapa demikian?
Karena jika makna ini dibaca secara keseluruhan, maka “Al, li, li, hu”
kurang lebih maknanya adalah ‘Sesuatu, yang baginya diperuntukkan, dan
sesuatu ini diperuntukkan, untuk Dia.” Jadi artinya secara sederhana
adalah, ‘(simbol) ini diperuntukkan, dan permisalan ini diperuntukkan,
untuk Dia (yang tak bernama).”
Dia yang asli, sebagai zat (entitas), sama sekali tak bisa diliputi oleh sebuah nama.
C. Hadits Rasulullah yang mengandung simbol serupa.
Kalau kita teliti dalam memperhatikan hadits berikut ini, kita akan
mengerti bahwa Rasulullah bukan orang yang berkata dengan ‘pendapatnya
sendiri’. Orang dalam tingkatan maqam seperti Rasulullan saw.,
tentulah setiap tindak tanduk dan perkataanya sudah sepenuhnya dalam
bimbingan Allah swt. Tampak dari demikian akuratnya simbol-simbol yang
digunakan, meskipun jika kita baca secara sepintas hadits ini sangatlah
sederhana dan tidak bermakna dalam. Hanya kalau kita teliti, betapa
dalam dan akuratnya simbol yang Beliau gunakan dalam kata- katanya.
Kita lihat hadits berikut ini:
Diriwayatkan dari riwayat Abu Hurairah ra.:
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?”
Rasulullah saw. bersabda, “Apakah kalian terhalang melihat bulan di malam purnama?”
Para sahabat menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.”
Rasulullah saw. bersabda, “Apakah kalian terhalang melihat matahari yang tidak tertutup awan?”
Mereka menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.”
Rasulullah saw. bersabda, “Seperti itulah kalian akan melihat Allah. Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ia kelak mengikuti sembahannya itu. Orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, orang yang menyembah berhala mengikuti berhala.”
[H. R. Muslim no. 267]
Sepintas, hadits ini hanya berisi tentang melihat Allah di hari
kiamat. Tapi kalau kita teliti lebih jauh perumpamaan yang digunakan
dengan kacamata ilmu astronomi yang pada saat Rasul mengatakan hadits
tersebut ilmu ini belum semaju sekarang, sebenarnya hadits ini juga
menjelaskan bahwa ada bagian dari ‘Dia’ yang tak akan bisa kita kenali.
Kita cermati perumpamaan bulan purnama yang dipakai beliau dalam
hadits ini.
Sebagaimana kita tahu, pada saat bulan purnama di langit malam yang
cerah, kita bisa melihat bulan ‘seluruhnya’. Kata seluruhnya ini saya
beri tanda kutip, karena memang ‘seluruhnya’ itu semu. Kita melihat
–seakan-akan– bulan tampak seluruhnya dari mata kita. Kita, saat itu,
seakan-akan bisa ‘mengenal’ bulan seluruhnya.
Nah, di zaman modern ini, kita tentu mengetahui bahwa bulan adalah
sebuah ‘satelit,’ sebuah planet kecil yang mengelilingi bumi. Periode
waktu rotasi bulan, sama persis dengan periode lamanya bulan
mengelilingi bumi. Jadi, permukaan bulan yang menghadap bumi setiap
saat adalah sisi yang sama persis, yang itu-itu saja. Tidak berubah.
Demikian pula, ada sisi lain di balik bulan yang akan selalu tidak
tampak dari bumi, yang setiap saat akan selalu membelakangi bumi, tidak
akan pernah terlihat dari bumi. Dengan kata lain, jika kita berdiri di
sisi bulan yang terlihat dari bumi, maka meski bulan berotasi sambil
terus mengorbit mengelilingi bumi, kita akan selalu terlihat dari bumi.
Sebaliknya, jika kita berdiri di sisi bulan yang tidak terlihat dari
bumi, maka kita tidak akan pernah terlihat dari bumi pula.
Gambar jelasnya seperti ini:
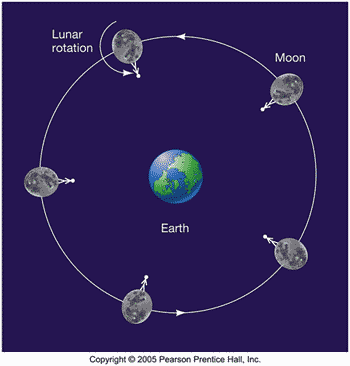
Inilah sebabnya, sejak zaman manusia pertama ada hingga sekarang,
permukaan bulan yang tampak dari bumi kelihatannya tak pernah berubah,
karena sisi yang menghadap bumi senantiasa merupakan sisi yang sama.
Di hadits ini, Rasul memisalkan Allah sebagai bulan purnama. Bulan,
sebagaimana telah dijelaskan tadi, hanya ada satu sisi yang bisa
terlihat oleh kita. Jadi, secara tersirat dalam hadits tadi, Rasulullah
juga menjelaskan bahwa sesempurna- sempurnanya pengenalan seseorang
akan Allah (seperti orang yang telah mencapai maqam para sahabat Beliau
itu), sebenarnya barulah satu sisi dari Dia saja. Sisi yang memang Dia
hadapkan sepenuhnya kepada manusia. Sisi inilah yang dalam bahasa agama
disebut sebagai “Wajah-Nya.”
Tapi sampai kapan pun, akan tetap ada sisi lain dari Dia yang tidak
akan pernah terpahami oleh manusia (karena Dia sesungguhnya Maha Tak
Terbatas). Dan keseluruhan ‘Dia’ secara utuh, yang bisa dikenali dan
yang tidak, dalam bahasa agama disebut “Zat-Nya,” atau entitas-Nya, secara keseluruhan.
Jadi sekarang kita bisa lebih memahami, jika dalam Al-Qur’an atau doa
yang diajarkan Rasulullah mengandung kata-kata ‘wajah Allah’ atau
‘wajah-Nya (wajhahu)‘, maka itu bukan berarti bahwa Dia
memiliki wajah di depan kepala seperti kita. Itu maknanya adalah,
konteks ‘Dia’ dalam kalimat itu adalah pada sisi yang masih bisa kita
kenali. Sedangkan Zat-Nya yang utuh tidak akan pernah bisa kenali.
Mengenai zat-Nya, Al-Qur’an sendiri cukup menerangkan seperti ini:
“…laysa kamitslihi syay’un”
“… dan tiada sesuatupun yang bisa dijadikan permisalan untuk Dia.” (QS. 42 : 11)
Rasul melarang manusia memikirkan zat-Nya, dalam sabdanya,
“Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, dan jangan sekali-kali
berfikir tentang zat-Nya, sebab kalian akan binasa.” Bahkan Beliau
sendiri pun mengakui bahwa dirinya tidak memahami ‘Dia’ dalam konteks
zat, sebab dalam sabdanya Beliau menjelaskan, “sesungguhnya aku adalah
orang yang bodoh dalam ihwal zat Tuhanku.”
Kembali pada contoh bulan di atas. Bulan, sesuai periode edarnya,
akan tampak dari bumi bermacam-macam bentuknya, mulai dari bulan hitam
(bulan tak tampak), bulan hilal, bulan sabit, bulan setengah, hingga
bulan purnama.
Sebenarnya demikian pula pengenalan manusia kepada Allah ta’ala. Ada
yang tidak mengenal sama sekali (bulan hitam), ada yang pengenalannya
setipis hilal, ada yang pengenalannya seperti bulan setengah, dan ada
pula yang pengenalannya terhadap Allah telah ‘purnama’. Namun demikian,
sebagai zat tetap saja Dia tidak akan pernah terpahami sepenuhnya oleh
manusia, karena Dia adalah Maha Tak Terbatas.

Dari sini saja, kita bisa mengerti bahwa faham panteisme,
atau menyatunya Tuhan dan manusia sebagaimana yang dituduhkan kepada
kaum sufi, adalah tidak tepat. Tentu mustahil sesuatu yang tak terbatas
bisa terlingkupi oleh sesuatu yang terbatas.
Agaknya yang dituduhkan pada kaum sufi sebagai panteisme atau
penyatuan, sebenarnya yang terjadi adalah ‘sirna kediriannya’. Contohnya
seperti cahaya lilin yang akan lenyap cahayanya jika diletakkan di
bawah cahaya matahari. Ini masih perlu kita kaji lebih lanjut. Atau
paling tidak, agaknya tidak semua sufi meyakini panteisme. Seperti kata
teman saya: “Sufi, pantheisme? Sufi yang mana dulu, nih?”
Sekarang, dari cara Rasulullah memberikan contoh pada dalam hadits di
atas, kita bisa lebih mengerti kira-kira sedalam apa akurasi hikmah
dari kata-kata seseorang jika telah ada dalam tingkatan maqam
seperti junjungan kita Rasulullah Muhammad saw. Tentu beliau tidak asal
ambil contoh saja, seperti ketika kita sedang berusaha menerangkan
sesuatu kepada orang lain. Sekarang semakin jelas pula bahwa segala
sesuatu dari diri Beliau telah ditetapkan dalam bimbingan Allah ta’ala,
bahkan sampai hal ‘sepele’ seperti mengambil contoh yang tepat ketika
menerangkan sebuah persoalan.
Juga sebagaimana hadits Rasulullah tadi, segala sesuatu dalam
ciptaan-Nya pun tidaklah semata-mata hanya sebagaimana yang tampak dari
luar. Allah tentu tidaklah sesederhana itu. Seperti hadits tadi, segala
sesuatu juga mengandung makna batin. Alam semesta, bulan, bintang, batu,
hewan, tumbuhan, manusia, syariat (ada syariat lahir dan tentu ada
syariat batin), dan lain sebagainya. Sedalam apa seseorang melihat
maknanya, tentu sangat tergantung pada kesucian qalbnya, sarana untuk
menerima ilmu dari-Nya.
Kini kita bisa sedikit lebih mengerti pula, seperti apa kira-kira kesucian qalb
Rasulullah saw, jika kata-kata Beliau mampu menyederhanakan kandungan
makna yang sedalam itu (itupun baru yang bisa kita ungkapkan) dalam
kesederhanaan simbol-simbol yang sangat akurat.
Kalau Al-Qur’an? Lebih tak bisa kita bayangkan lagi seperti apa sesungguhnya kedalaman kandungan makna Al-Qur’an.
Semoga bermanfaat, 